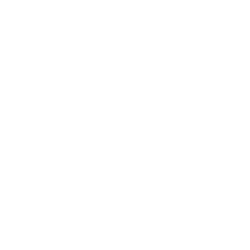Oleh: Zahra Mugny Aulia
(Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah/ Santri Pondok Pesantren Mahasiswa Darussalam)
Sejak lahirnya (1920) sampai sekarang (1990), kesusastraan Indonesia modern selalu berkembang. Dengan demikian, hal ini membuat adanya persambungan sejarah sastra Indonesia, baik dalam ragam prosa maupun puisi. Sampai sekarang, yang merupakan sajak Indonesia modern yang pertama adalah sajak “Tanah Air” yang ditulis oleh M. Jamin (Muhammad Yamin), terdapat dalam Jong Sumatra No. 4, Tahnun III, April 1920 (Pradopo, 2012: 131). Sebelum M. Yamin menulis sajak “Tanah Air” itu, di Indonesia sudah ada satra Melayu lama, khususnya puisi Melayu lama yang ragam utamanya berupa Pantun dan Syair yang merupakan puisi “tradisional” atau “konvensional”
Peranan sastra, baik fiksi maupun nonfiksi, dalam mengungkapkan aspek-aspek kebudayaan, hampir sama dengan disiplin yang lain, seperti: antropologi, sosiologi, psikologi, arkeologi, sejarah, dan ilmu bahasa. Artinya, relevansi masing-masing disiplin tergantung dari tujuan penelitian, objek yang dikaji, teori dan metode yang dimanfaatkan. Sastra modern, seperti: novel, puisi, dan drama, demikian juga sastra lama, seperti: kakawin, babad, dongeng, dan cerita rakyat, termasuk peribahasa, gosip, humor, dan berbagai tradisi lisan yang lain, merupakan objek studi kultural yang kaya dengan nilai.
Generasi millenial merupakan generasi pengguna media sosial, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok, ekonomi, eksistensi bahkan pencarian informasi (Ainiyah, 2018: 223). Pastinya remaja millenial millenial merupakan remaja millenial yang sangat akrab dengan teknologi internet dimana handphone dengan system android yang menawarkan fitur-fitur dan aplikasi yang memberi kemudahan bagi remaja millenial untuk mengakses informasi seperti yang mereka inginkan. Generasi millennial sangat tak bisa dipisahkan dari media social. Media Sosial adalah salah satu anak dari duniamaya yang saat ini telah menjadi sebuah trend yang memiliki dampak yang begitu kuat terhadap perkembangan pola fikir manusia.
Tidak jarang sekali pada zaman sekarang generasi millennial memanfaatkan media sosial sebagai bahan mengekspresikan diri. Bahkan untuk menjadi terkenal saja sekarang tidak susah, hanya dengan mengcover lagu lewat youtube orang bisa langsung terkenal, atau sering memposting kalimat-kalimat motivasi di akun instagram atau akun lainya sudah bisa disebut motivator atau ada pula musikalisasi puisi yaitu dengan memadukan antara musik dan puisi, bahkan kini banyak digemari. Kini orang-orang terutama remaja mulai belomba-lomba agar karyanya dilihat banyak orang, bahkan membuka lebar-lebar bentuk apresiasi dan kritik saran dari para penonton.
Seorang pemerhati tren digital dan remaja, menuliskan 4 alasan utama remaja menjadi maniak media sosial, seperti dilansir dalam situsPsychology Today, yaitu: (Tempo: 2013) Pertama, mendapatkan perhatian. Hasil penelitian dari Pew Research Center Study, AS, menunjukkan bahwa sebagian besar remaja berbagi informasi di sosial media. Berbagai informasi menjadi kunci bagi mereka untuk mendapatkan perhatian bagi diri mereka sendiri. Kedua, meminta pendapat. Remaja seringkali meminta pendapat dan persetujuan rekan-rekannya untuk memutuskan sesuatu. Itu wajar jika di dunia nyata. Namun, dengan adanya media sosial, mereka menjadi meminta pendapat untuk hal yang tidak penting. Contohnya, mereka akan semakin sering menggunggah foto untuk sekadar melihat bagaimana komentar rekan-rekannya. Semakin banyak pujian atau sekadar “Like” di Facebook akan membuat mereka merasa populer. Dengan kata lain, media sosial menjadi indikator kepopoleran meraka. Ada ‘kepuasan intrinsik’ pada remaja jika mereka populer di media social. Ketiga, menumbuhkan citra. Media sosial tidak akan mampu mendeskripsikan pribadi seorang pengguna secara utuh. Oleh sebab itu, remaja menjadikan media sosial penumbuh citra positif mereka. Remaja akan cenderung memberikan kesan yang baik saat di media sosial. Mereka berharap orang lain melihat mereka seperti apa yang mereka harapkan. Keempat, kecanduan media sosial. Mereka akan sulit mengalihkan pandang dari situ. Mereka ‘terjebak’ dalam lingkaran drama media sosial. Meskipun mereka terus mengeluh tentang ‘’drama’ dalam media sosial nyatanya mereka jugalah pelaku drama tersebut.
Tidak jarang juga banyak anak millennial yang berkomentar negative tentang sastra, terutama dalam puisi. Seperti yang dicontohkan oleh Dihlyz Yasir dalam blognya (Yasir, 2018): “Ketika seseorang nongkrong di kafe dengan buku puisi di tangannya, terlebih lagi jika seseorang itu adalah laki-laki berambut gondrong yang juga kebetulan seorang perokok aktif, maka suara spontan yang muncul dari sekitarnya adalah: “Bacaanmu kok puisi, sih, lagi galau ya?”, “wajahnya sangar kok bacaannya puisi?”, “Kok mau sih baca puisinya orang?” atau respon paling parah yang biasa diberikan oleh si penanya – setelah tahu bahwa seseorang yang ditanya itu membaca buku puisi – hanya sekedar: “Oh..”, lalu ditutup dengan raut wajah yang seolah-olah menganggap puisi itu tak lebih dari sekedar kumpulan kata-kata indah yang hanya cocok dikonsumsi laki-laki baperan.”
Dihlyz Yasir pun mengatakan, sikap yang memandang puisi sebagai hal yang cengeng ini bisa terjadi sebab dua hal. Pertama disebabkan oleh ketikdakpahaman mereka tentang apa itu puisi, dan yang kedua adalah, ketidaksadaran mereka bahwa pemahaman yang mengidentikkan puisi dengan kecengengan itu sebenarnya juga terbentuk oleh sejarah.
Di negara Inggris sendiri minat generasi millennial terhadap puisi melonjak. Penjualan buku puisi mencapai rekor tertingginya pada tahun 2018. The Guardian, Senin (21/1/2019), data dari Nielsen BookScan menunjukkan penjualan tumbuh lebih dari 12 persen pada tahun lalu. Di mana 1,3 juta volume buku puisi telah terjual pada tahun 2018, pendapatan bertambah hingga 12,3 juta euro dalam penjualan. Dua per tiga dari pembeli merupakan para pemuda yang umurnya di bawah 34 tahun, 41 persen berumur antara 13-22 tahun (Swastiningrum, 2019). Gadis remaja dan perempuan muda merupakan konsumen puisi terbesar. Andre Bredt dari Nielsen menjelaskan, penjualan buku puisi yang meledak karena adanya pergolakan dan konflik politik. Puisi dijadikan alat untuk memahami fenomena-fenomena tersebut dan sebagai alternatif untuk memahami dunia.
Untuk meminimalisasi generasi millennial yang belum menyukai karya sastra kini harus diatasi melalui pendekatan untuk menumbuhkan minat baca. Menurut Seno Gumira Ajidarma, ada tiga mitos sastra yang harus dihancurkan, Menurutnya, ini yang membuat sastra itu dijauhi dan membuat alergi (Saputra, 2018). Yang pertama, sastra itu curhat. Kedua, bahasa sastrawan itu mendayu-dayu, rumit, asing didengar, sehingga membuat sebagian pembaca yang jarang membaca karya sastra merasa bahwa sastra bukan bagian dari bacaannya. Ketiga, sastra itu berisi pedoman hidup, petuah-petuah, nasihat-nasihat.
Sedangkan menurut Budi Darma (Saputa, 2018), sastrawan yang juga Guru Besar Universitas Negeri Surabaya mengatakan, anggapan banyak anak muda tidak suka membaca itu tidak sepenuhnya betul. Dia mengatakan “Anak-anak muda ini sekarang berdiri di atas dua kaki. Yang pertama mereka sangat pandai dalam mengoperasionalkan gawai. Yang kedua mereka juga suka membaca buku, meskipun buku yang dibaca masih sesuai dengan umurnya, atau sesuai dengan selera masing-masing “.
Sastra di Indonesia pada tahun 2019 ini cukup meningkat, dengan adanya media sosial ini mempermudah para generasi millennial dalam mengunggah karya-karyanya di media sosial. Tapi, tidak semua anak millennial menyukai sastra terutama dalam puisi. Mereka yang tidak suka menganggap puisi sebagai kata-kata yang lebay atau yang lainya. Padahal di Inggis saja minat puisi melonjak drastis pada tahun 2018 oleh kalangan remaja. Menurut Seno Gumira Ajidarma harus ada mitos-mitos yang dihancurkan, agar meminimalisir para generasi millennial dalam menyukai sastra.