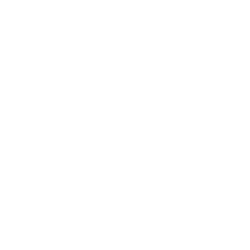Filsuf Denmark, Soren Kierkegarrd (1813-1855), menengarai hidup ini sebagai pilihan. Kalau tidak memilih “ini” ya memilih “itu” (either/or). Tidak memilih juga sebagai pilihan. Spektrum objek pilihan itu bisa dimulai dari yang paling mudah sehingga mudah pula menentukan pilihan, sampai yang sulit sehingga sangat sulit mau memilih yang mana. Pilihan paling sulit dalam khazanah kearifan Nusantara digambarkan ketika ketika kita dihadapkan pada buah simalakama, kalau dimakan sang ayah akan mati jika tidak dimakan sang ibu yang akan mati.
Diantara pilihan paling sulit bagi sebagian rakyat Indonesia baru-baru ini adalah saat harus mencoblos surat suara di pemilihan kepala daerah (pilkada). Mengapa ini disebut pilihan paling sulit?. Pilkada secara ideal dimaksudkan untuk berburu kepala daerah yang betul-betul mau menyerap aspirasi rakyat diteritorial kekuasaan mereka dan membawa rakyat mereka kepada penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan, diantaranya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Seringkali realitas berbicara berbanding terbalik dari idealitas. Seorang kepala daerah yang das solen-nya mestinya berupaya keras menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya, secara das sein justru acapkali menjadi “pemberi harapan palsu” (PHP) mengenai kesejahtraan rakyat ketika gegap gempita kampanye. Tidak jarang calon kepala daerah setelah terpilih justru melakonkan apa yang disebut filsuf Inggris Thomas Hobbes (1588-1679) sebagai “homo homini lupus” (manusia sebagai srigala/pemangsa yang lain).
Banyak kepala daerah yang kemudian menghuni “hotel prodeo” karena terlibat kasus korupsi merupakan salah satu penanda (qarinah) bagaimana pemimpin yang seharusnya menghidangkan makanan untuk rakyatnya justru menjadi pemangsa yang rakus yang menghabiskan hidangan makanan itu untuk diri, kroni, dan keluarganya.
Kritik Sarkastik
Tidak mengherankan jika kemudian di media sosial banyak kritik kepada para pejabat, kepala daerah, dan wakil rakyat pada umumnya. Kritik itu ada yang bernada halus, ada yang sangat sarkastik. Kritik yang bernada halus, misalnya yang mengomparasikan antara pilkada dan pilkabe (aslinya:pil KB). Yang kedua itu kalau lupa malah jadi. Sedangkan yang pertama kalau jadi malah lupa.
Kritik yang bernada sarkastik, misalnya muncul istilah “Pancagila” atau “lima kegilaan”. Pancagila sejatinya merupakan kritik atas antiklimaks head to head dari pelaksanaan Pancasila di negeri ini. Sila pertama yang seharusnya “Ketuhanan Yang Maha Esa” berubah menjadi “Keuangan yang maha kuasa”. Sila kedua yang mestinya “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi “Korupsi yang adil dan merata”. Sila ketiga yang idealnya “Persatuan Indonesia” bermetamorfosis menjadi “persatuan mafia hukum Indonesia”. Sila keempat yang seharusnya “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” berganti rupa menjadi “Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan”. Sila terakhir, kelima, yang mestinya “Keadilan, social bagi seluruh rakyat Indonesia” berubah menjadi “Kenyamanan social bagi seluruh keluarga pejabat dan wakil rakyat”. Dengan demikian, Pancasila yang mencakup kata kunci “keuangan, korupsi, mafia, kekuasaan, dan kenyamanan pejabat/wakil rakyat” sudah menjadi “counter culture” bagi Pancasila di negeri ini.
Jika meminjam kacamata kelirumologinya Jaya Suprana, Pancagila merupakan bentuk kritik yang bagi mereka yang punya sensitivitas tinggi, sangat sarkastis, menghujam dalam serta mengena.
Meskipun sudah sering muncul kritik pedas kepada para wakil rakyat, pejabat, atau, memakai khazanah kearifan Jawa, “bungen-tuwa”, mlebu tengen, metu kiwa: masuk telinga kanan, keluar lewat telinga kiri, alias tidak berefek.
Drama “Papa minta saham” yang akhir-akhir ini menjadi fenomenal karena konotasi penyoratifnya hanyalah salah satu bagaimana mereka yang mendapat titipan suara rakyat (vox populi) justru mengamalkan Pancagila. “papa minta saham” dalam wujud lain sudah banyak presedennya dan mungkin masih akan berekor panjang antesedennya. Jika sudah demikian, pilkada sebagai upaya menitipkan suara, bagi sebagian rakyat Indonesia di banyak daerah, masih menjadi pilihan sangat sulit.
Rakyat dihadapkan pada buah simalakama: jika tidak mencoblos berarti menegasikan hak diri; jika mencoblos, sering justru menjadi jalan lain untuk “bunuh diri” karena “ngopeni macan luwe” (memelihara harimau lapar) yang justru “memangsa” pemberi suara degan beragam rupa cara.