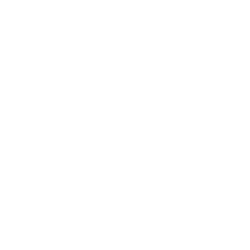Oleh: Abdul Ghofur (Staf Akademik FITK)

Tidak asing di telinga masyarakat Indonesia tentang kebesaran sosok Suwardi Suryaningrat atau yang akrab disebut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Menteri Pendidikan Nasional RI ke-1. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu Pahlawan Nasional yang memiliki peran penting dalam memajukan dan peletak dasar pengembangan pendidikan Indonesia.
Ki Hajar sangat dikenal melalui 3 jargon khas pendidikan. Sehingga jargon yang berbahasa Jawa tersebut menjadi semboyan yang ditulis di sekolah-sekolah, baik di dinding kelas, ruang guru, prasasti di halaman sekolah, dan lainnya. Tentu semboyan tersebut digadang-gadang tidak hanya penghias atau pelengkap semata, namun mampu terimplemantasi dalam praktik nyata pendidikan Indonesia.
Ya, jargon tersebut yang pertama berbunyi Ing ngarsa sung tuladha yang berarti di depan sebagai pemberi contoh. Kedua Ing madya mangun karsa yang berarti di tengah memberikan semangat. Dan yang terakhir ketiga Tut wuri handayani artinya di belakang memberikan dorongan dan kekuatan.
Konsep tersebut kiranya masih relevan bila dikaitkan dengan pengembangan pendidikan ideal di negeri ini. Semboyan yang dijadikan sebagai motto Taman Siswa tersebut, bahkan untuk Tut wuri handayani hingga kini tersemat indah dalam logo resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Namun, kenyataannya jauh panggang dari api, ketiga semboyan yang diharapkan mampu teraplikasikan dengan baik harus menemui kenyataan pahit. Globalisasi yang kian mengganas di setiap lini kehidupan manusia, termasuk pendidikan, membendung dan menghalangi konsep tersebut terimplementasi dengan baik. Pada akhirnya tujuan mulia dari konsep tersebut seakan terbelokkan, tergantikan kebutuhan sesaat dan individualis para pemegang kepentingan.
Sebuah Kontradiksi
Taruhlah pada semboyan pertama, Ing ngarsa sung tuladha kini telah berubah dan bergeser menjadi Ing ngarsa numpuk banda yang artinya yang di depan hanya mengumpulkan harta. Para pangarsa (baca: pemuka), baik agama, ormas, maupun negara, dan pemuka lainnya dewasa ini terlihat seringkali menampilkan kepribadian yang tak layak dicontoh. Kasus-kasus besar dan memalukan menerpa para pemuka dan anehnya tidak ada raut penyesalan di wajah-wajah mereka, bahkan ketika ditangkap penegak hukum, seringai senyum dan lambaian tangan dengan santainya tergurai. Kasus korupsi, suap, pencucian uang, dan berbagai aktivitas memperkaya diri lainnya yang dilakukan oleh para pemuka, sudah menggunung dan menggurita serta seakan dianggap menjadi hal yang wajar dan biasa saja.
Secara umum dapat pula dicermati bahwa kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala bentuknya telah dengan jelas mengidapi para pejabat publik negara. Baru-baru ini kasus dicatutnya beberapa nama pejabat publik dalam Panama Papers menjadi contoh konkretnya. Para agamawan pun sering terbelenggu pada pemahaman sempit terhadap agama, pembuatan fatwa yang serampangan, adanya komersialisasi agama melalui berbagai hal yang dihubung-hubungkan sebagai sesuatu yang Islami, misalnya, berita yang sedang hangat beberapa waktu lalu tentang wacana sertifikasi jilbab halal. Hal itu menambah daftar lengkap kuatnya praktik semboyan Ing ngarsa numpuk banda.
Pada semboyan kedua Ing madya mangun karsa, namun kenyataannya bergeser pada Ing madya pada sulaya artinya di tengah salah kaprah. Para penengah yang diharapkan mampu memberi semangat dan spirit perjuangan namun apa daya terbelenggu pada ketidakteraturan sistem. Padahal bukankah mereka seharusya berkiprah sebagai penghubung dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Para panengah ini seakan menjadi kalap dan salah kaprah, karena para pangarsa-nya yang telah terjerumus pada nafsu sesaat menumpuk-numpuk harta sebanyak-banyaknya. Efek domino menyebabkan para penengah ini kalang kabut, sikut sana sini untuk mampu mempertahankan kehidupan dan eksistensinya.
Pada semboyan ketiga Tut wuri handayani seakan bergeser menjadi Tut wuri anyrekali, artinya di belakang saling menjatuhkan. Para kelas grass root inilah yang menerima efek domino paling nyata dari polah tingkah dan tidak bermutunya kualitas para pemuka dan penengah. Para kelas bawah yang seharusnya mampu memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang, namun “dipaksa” untuk saling jegal menjegal demi memenuhi hasrat dan kebutuhan individual masing-masing. Mereka dengan segala keterbatasannya terus berupaya memenuhi kebutuhan dan eksistensinya tentunya sebagai masyarakat kelas bawah. Dalam konteks ekonomi berkenaan jegal menjegal ini sering terdengar celetukan “mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal”.
Mulai dari Diri Sendiri
Demikian tragis dan sengitkah pengaruh dari globalisasi yang telah meluluh lantahkan bangunan indah yang telah diikhtiarkan dan dirintis oleh Ki Hajar Dewantara. Sedemikian rupa konsep tersebut terputarbalikkan di era modern ini. Maka diperlukan solusi bijak aplikatif dari semua pihak. Utamanya kita sebagai individu perlu menjadi pelopor dan promotor untuk kembali me-refresh implementasi nilai-nilai luhur semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut.
Pada bidang pendidikan, sekolah perlu mengkampanyekan kembali nilai-nilai tersebut, sehingga tidak hanya menjadi hiasan atau pemoles dinding semata. Namun mampu dimaknai dan diaplikasikan sebagai suatu pembiasaan sehingga menjadi budaya sekolah. Pendidik, peserta didik, dan seluruh komponen pendidikan hendaknya berharmoni bersama memaknai dan mempraktikkan ulang dengan baik konsep yang mulai pudar tersebut.
Sehingga pada akhirnya diharapkan mampu terbentuk karakter individu yang empan papan (memperhatikan isi dan tempat/kondisi). Setiap individu mampu menempatkan dirinya apakah sebagai pemuka, penengah, atau orang yang di belakang. Dengan mengetahui posisinya masing-masing, maka setiap individu diikhtiarkan mampu berandil dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tenteram sesuai piwulang (ajaran) yang telah diajarkan Ki Hajar Dewantara. Semoga.